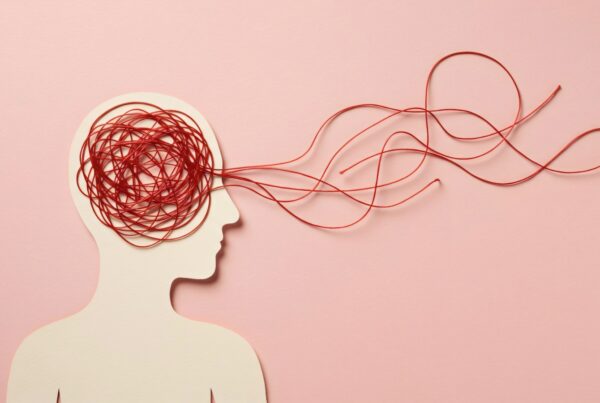Terpantik artikel menarik dari HBR (Harvard Business Review) yang ditulis oleh Dena Dinham Smith, berjudul Leading Is Emotionally Draining, Here’s How To Recover, July 11, 2025. Menurut penulis, yang merupakan Executive Coach, pemimpin saat ini sering dihadapkan dengan banyak tantangan yang melibatkan pekerjaan yang “menguras” emosi (emotional depletion). Dalam kasus yang lebih berat dan kronis, biasanya disebut dengan burnout, atau kelelahan mental.
Terkurasnya emosi (emotional depletion) digambarkan oleh Dena sebagai konsekuensi pajak yang harus dibayar (significant tax) atas peran kepemimpinan di dunia modern. Kelelahan akibat terkurasnya emosi digambarkan sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, sama seperti pajak. Konon di dunia ini ada dua hal yang tidak bisa dihindari yaitu pajak dan kematian. Menurutnya, pemulihan dari terkurasnya emosi sudah bukan lagi barang mewah tapi telah menjadi keharusan di jaman yang serba cepat ini.
Sebelum mengenal model kepemimpinan berbasis kesadaran Sigma Leadership , tentu saya pun mengalami emotional depletion seperti yang digambarkan oleh Dena. Lebih dari dua puluh tahun menjadi pemimpin dalam versi dan cakupan peran, sebagai ibu, sebagai kepala rumah tangga, maupun sebagai karyawan di korporasi. Siklus kelelahan emosi hadir dengan berbagai intensitasnya, paling tinggi biasanya terjadi masa lebaran. Menghadapi ketidakpastian asisten rumah tangga, sementara ada dua balita yang perlu dijaga bersamaan dengan tingginya beban pekerjaan beserta dinamikanya di korporasi. Kelelahan emosi yang saya alami memang bisa dipulihkan dengan berbagai cara, tetapi efeknya hanya berlangsung sementara saja, tidak pernah tuntas. Dan di kemudian hari akan terulang kembali siklus yang sama persis, melelahkan dan menguras emosi. Secara ekonomi, dibutuhkan pos khusus pemulihan di setiap siklusnya, walaupun tidak pernah menjamin kesehatan yang langgeng di masa depan.
Saya merasa sangat beruntung karena kemudian mengenal model kepemimpinan berbasis kesadaran Sigma Leadership, ketika tercebur dalam arena praktik atau magang menjadi pemimpin, dengan cakupan pekerjaan yang berkali-kali lipat lebih serius dan kompleks. Memang benar diakui bahwa menjadi pemimpin baik bagi diri sendiri, bagi keluarga, sekelompok teman, maupun organisasi, sepaket dengan konsekuensi berupa tanggung jawab, tantangan dan risikonya masing-masing. Semakin luas dan kompleks cakupan pekerjaan, maka dinamika dan tantangan akan semakin rumit dan ramai.
Dengan menjalankan rumusan dari kepemimpinan berbasis kesadaran Sigma, ternyata saya tidak perlu lagi mengalami kelelahan akibat emosi yang terkuras. Gejolak emosi yang muncul ketika berdinamika, tidak perlu lagi menguras energi dan perhatian yang menyebabkan emotional depletion. Seperti ketika menghadapi rekan kerja yang ngeyel, anak buah yang tidak mengerti budaya kerja, karyawan pembangkang, staf yang malas dan underperform, target yang belum tercapai, kinerja yang rendah, recovery kerusakan akibat kinerja yang buruk, dan sebagainya. Membutuhkan kekuatan mental dan energi yang jernih serta stabil, untuk menghadapi ramainya dinamika yang membutuhkan solusi serta langkah pemulihan. Kemampuan mengelola diri dengan cara yang tepat, memastikan agar tidak perlu membuang energi dan waktu bagi pemulihan diri yang kelelahan. Sehingga mampu mencurahkan perhatian kepada solusi tepat guna dan meminimalkan dampak destruktif bagi diri sendiri maupun pihak-pihak yang terkait.
Dinamika tentu tidak akan pernah lenyap, maka yang dibutuhkan adalah keterampilan dalam mengelola diri, termasuk mengelola pola pikir dan emosi ketika menghadapi tantangan. Dengan praktik mindfulness, saya mampu menjaga konsistensi kestabilan mental (mental state) serta kejernihan kesadaran. Menciptakan kekuatan sebagai penyangga kesetimbangan mental dan emosi melalui rumusan dalam kepemimpinan Sigma dengan mengasah keterampilan dalam mengelola pola pikir (mind management). Bagi saya, keterampilan ini merupakan Essential skill yang perlu diasah untuk mencegah emotional depletion dan burnout , serta mengelola gejolak emosi yang biasanya dianggap sebagai kewajaran dan kenormalan umum, terutama dalam ruang profesionalisme.
Yang pasti, saya tidak perlu lagi mengalami kelelahan akibat roller coaster emosional, dan tidak perlu lagi mencemari kesehatan mental, emosi dan fisik akibat menjalankan peran sebagai pemimpin. Sekaligus mencegah potensi degradasi kesehatan di masa depan.
Ada yang punya pengalaman serupa?
“Great leaders are defined by the presence of self growth” ~Sigma Leadership
Keisari Pieta
Chief Mentor The Avalon Consulting
6 Agustus 2025
Burn-out atau ngebul, merupakan kondisi mental emosional yang sangat dekat dengan kehidupan saya sehari-hari sebagai seorang pemimpin.
Kalau banyak yang mengenal kelelahan mental sejak mulai memasuki usia masuk bekerja di perusahaan, seingat saya, saya kenal dengan kelelahan ini sejak di bangku sekolah. Bedanya, dulu saya tidak tahu kalau kondisi itu adalah kondisi ngebul/kelelahan mental/burn-out.
Saya mengira kondisi kepala ngebul kelelahan itu adalah bentuk ketidakmampuan saya. Ketidakmampuan dalam memproses ilmu pengetahuan, dalam mengasah skill, dalam berperforma baik, dalam menjalani semua aktivitas sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler lengkap dengan beragam les bahasa-musik-dll yang mewarnai hari-hari.
Bahkan setelah masuk ke lingkungan kerja pun, kondisi kepala ngebul yang ditandai dengan kepala yang sakit itu saya kenali sebagai bentuk kekalahan diri terhadap situasi yang saya hadapi. Ketidakmampuan saya untuk terus menerus berada dalam kondisi fisik yang prima dan mampu menyelesaikan semua tugas kantor yang diberikan bahkan men-deliver lebih dari yang diharapkan itu saya anggap sebagi bentuk kompetensi diri yang kurang.
Jadi kalau saya terserang pusing saat bekerja (yang setelah saya kaji kembali selalu terjadi setiap hari, berkali-kali, bahkan sepanjang hari) itu adalah hal yang harus saya lawan. Saya harus memaksa diri saya agar mampu. Karena kalau tidak mampu berarti saya kalah dalam persaingan, dan hal tersebut sangat tidak menyenangkan ego saya. I don’t want to be a loser di dalam pekerjaan – I have to deliver beyond what is expected. Wah pokoknya sangat ambisius. Keberhasilan saya definisikan sebagai kesuksesan dalam karir, dalam citra diri, pengakuan diri, dan tentunya dalam seberapa cepat pundi-pundi bisa terkumpul.
Apalagi saat saya mulai menduduki kursi sebagai seorang pemimpin. Rasanya beban bertambah. Tidak hanya bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, namun saya juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan tim. Saya perlu mengatur ritme kerja tim, membagi tugas dengan bijaksana, membangun sistem/cara kerja yang efefktif, yang ujungnya adalah memberikan hasil kerja yang memuaskan bagi perusahaan. Semakin luas cakupan pekerjaan saya dan interaksi dengan semakin banyak orang, membuat saya lebih ngoyo, lebih banyak penyebab ngebul, lebih lelah secara mental emosional.
Baru sekitar 1 tahun yang lalu saya tahu bahwa kondisi kepala pusing itu adalah kondisi burn-out atau kondisi ngebul. Aha momen yang sangat berkesan bagi saya. Loh, hal yang sangat lumrah, sangat harian, sangat biasa saja saya alami setiap hari ini yang disebut ngebul? Disebut burn-out? Ah yang bener aja? Rasanya nggak kece, nggak keren, dan nggak banget. Tidak mudah untuk mengenali dan mengakui bahwa saya adalah pasien ngebul.
Pantesan, kalau dulu pulang sekolah/les, pulang ngantor selalu rasanya cape banget, padahal cuma duduk-duduk aja di depan laptop, jalan ke ruang meeting untuk meeting, jalan ke kantin untuk makan, pergerakan yang sangat minim, tapi otak kayak habis perang. Pantesan kok sering banget ruwet sendiri, otak kusut, memikirkan/mengerjakan sesuatu bisa sangat micro-detail yang terkadang tidak dibutuhkan — akhirnya ya cape sendiri.
Tentu saja tidak hanya saya yang lelah, tapi juga seluruh tim kerja saya karena terkena imbas dari keruwetan saya yang tidak diperlukan itu. Mengenang masa ini, saya jadi sadar kalau saya telah mengakibatkan burn-out bagi pihak lain juga. Seorang pemimpin yang ngebul menyebabkan tim nya ngebul semua. Domino’s effect yang nyata. Tidak hanya menyiksa diri sendiri, tetapi juga menyiksa orang lain. Kejam dengan diri sendiri, kejam dengan orang lain.
Perjalanan mengenali ngebul ini berjalan perlahan. Kondisi pusing menjadi indikator awal yang saya pakai. Di awal tahunya tiba-tiba sudah pusing berat. Kalau dulu sudah pusing juga terus hajar saja (tidak boleh kalah dengan pusing dong), perlahan saya ubah ke kalau sudah pusing maka ambil jeda untuk bermeditasi. Sesi meditasi yang selalu berujung ketiduran. Ya gimana nggak tidur, wong lelah otaknya. Setelah tidur sebentar, rasanya otak jadi lebih bisa ‘dipakai’ lagi.
Sampai saat saya menuliskan sharing ini, saya masih jadi langganan ngebul. Bedanya saya sudah lebih bisa mendeteksi ngebul lebih dini, jadi sebelum pusing akut sudah stop dulu untuk bermeditasi (masih banyak bablasnya sih). Saya mulai membiasakan diri untuk lebih mindful, lebih mau mengenali kapasitas dan kebutuhan diri — tidak dipaksa kerja rodi terus. Dulu saya kuat-kuat saja untuk meeting 2-3 jam dan back-to-back tiada henti, bahkan menurut saya itu adalah hal yang wajar dilakukan karena itulah cara bertotalitas.
Sekarang sudah tidak mau lagi menyiksa diri seperti itu. Meeting maksimal 1-1.5 jam lalu saya beri jeda dulu 30-60 menit untuk meditasi sebelum siap meeting berikutnya. Loh? Jadi kurang produktif dong? Kata siapa? Nyatanya ya enggak juga.
Saya tetap bisa men-deliver jumlah pekerjaan yang sama, bahkan mungkin lebih karena kualitas kerja saya lebih baik dibanding saat ngebul tiada henti itu. Saya jadi lebih tahu mana yang perlu dikerjakan dulu, sampai sedetail apa yang perlu dipikirkan/didiskusikan, lebih mau untuk berfokus pada tujuan pekerjaan, tidak hanya sekadar mengerjakan mengejar kesempurnaan/idealisme pribadi.
Saya lebih punya daya tahan untuk menjalani berbagai peran dan pekerjaan yang secara kuantitas terus bertambah. Diri ini jadi karet yang lebih lentur dan tidak gampang putus. Stamina yang tadinya habis terkuras untuk ngeyel berontak terhadap situasi kondisi yang tidak ideal jadi lebih terkelola (tidak boros energi).
Emosi saya lebih terkontrol. Kelelahan karena terlalu sibuk beremosi/hanyut dalam emosi negatif terhadap kondisi tidak ideal yang selalu terjadi di pekerjaan juga berkurang. Saya tidak lalu berlarut-larut dalam emosi destruktif (marah, kesal) saat terjadi hal yang tidak sesuai dengan ego saya. Karyawan yang tidak bekerja sesuai arahan, partner kerja yang bergerak semaunya, belum lagi vendor atau pihak ke-3 yang cara kerja atau attitude nya tidak sesuai dengan standar idealisme saya.
Dengan kondisi stamina mental emosional yang lebih prima, saya bisa mengerjakan lebih banyak hal tanpa mengurangi akurasi dan efektivitasnya.
Tentunya masih jauh dari sempurna karena ngebul masih menjadi makanan sehari-hari, tapi langkah perbaikan terhadap kesehatan mental yang saya lakukan mulai bisa saya saksikan dampaknya lewat pembiasan hidup yang lebih mindful. Kalau dulu mode nya bertahan dan melawan, setidaknya sekarang mulai bergeser ke berdamai dan menjalani.
Saya flashback saat kuliah di AS, teringat menjalani ngebul pertama saat saya tiap hari harus ke library untuk belajar. Saat itu rasanya baru ngerasain bener-bener belajar ya saat ambil S2 ini. Sebelumnya relatif santai, nggak ngoyo.
Saat itu kayaknya sempat ketiduran di library juga. Untung library di kampus tidak buka 24 jam jadi saya harus pulang. Kalau tidak mungkin saya nginep di library. Kompensasinya? kalau libur mesti healing jalan-jalan naik mobil keliling AS.
Pas kerja, burnout atau ngebul dialami saat mesti mengganti sistem pembayaran baru dan memastikan berjalan baik. Sehingga pulang dari kantor bisa jam 2-3 pagi. Setelah sistem berjalan pun tiap hari Rabu (saya ingat) dimana payment day, mesti pulang jam 21 an. Saya ingat badan jadi lepek karena AC sudah mati.
Juga diawal Zsazsa (anak saya) baru lahir dan harus begadang tiap malam. Akhirnya ngantuk terus di kantor. Pernah kejadian saya ketiduran dibawah meja dan ketahuan boss bule, untung nggak marah ????.
Ya gitu, yang namanya burnout atau ngebul waktu itu adalah bagian dari pekerjaan. Malah untuk jadi “excel” (high performance employees) ya harus begitu. Kalau istilah kerennya “doing extra mile”. Semakin pulang malam dianggap keren karena dianggap pekerja keras.
Untungnya waktu itu juga kemudian kenal olah raga, jadi ada kompensasinya. Demikian pengalaman ngebul saya…
Bekerja dan bahagia dulu untuk saya rasanya dua kata yang tak bisa disandingkan bersama. Saya harus memilih salah satu, kalo kerja itu rasanya gak mungkin bisa bahagia, dan kalau mau bahagia itu sama dengan tidak mengerjakan apapun, hanya santai mengisi waktu. Mungkin cukup absurd terdengarnya. Tapi ada sebuah perjalanan panjang yang melatarinya.
Pengalaman kerja saya diawali dengan menjadi reporter media berita online, dimana kecepatan adalah harga mati. Tak ada proses mencerna dan memahami secara utuh, apalagi mencari data dengan riset yang lengkap, karena yang dikejar adalah kecepatan berita untuk segera tayang. Persaingan dengan media online lainnya membuat pengalaman mencari narasumber dan mengumpulkan bahan berita semakin ketat. Saya bisa dimaki-maki oleh koordinator liputan saya bila media tetangga naikin berita yang sedang saya liput itu dalam waktu yang lebih cepat. Kerja adalah stress, berpacu dengan waktu, setiap saat dalam mode stand by.
Masuk ke dunia birokrasi menjadi staf seorang pejabat publik ternyata mengulang ritme kerja yang persis sama. Kecepatan, kesigapan, dan selalu siap sedia dipanggil bila dibutuhkan atasan itu membuat saya rasanya sulit menikmati waktu saat ini disini. Pikiran selalu berputar cepat, menyiapkan ini itu dan selalu siap dengan mental siaga. Panggilan mendadak setiap saat bisa membuyarkan agenda yang sudah disusun ataupun kegiatan yang sedang dijalani. Lagi-lagi bekerja adalah stress, dan membutuhkan ruang dan waktu untuk melarikan sejenak demi menjaga kewarasan. Sekedar nongkrong menikmati musik di akhir pekan, atau ke salon menyenangkan diri sejenak, meski tentu dengan kondisi handphone tetap stand by on call.
Ketika menikah dan punya anak balita saya mencari pekerjaan dengan jam kerja yang lebih teratur. Akhirnya mendarat di sebuah proyek yang didanai lembaga asing dengan jam kerja sangat tepat waktu, dan sabtu minggu juga tidak diganggu pekerjaan. Sebuah kemewahan. Tapi apakah kemudian saya bahagia dan bisa menikmati waktu ? Ternyata peran menjadi ibu bekerja dengan anak balita juga memberikan stressnya sendiri belum persoalan lain dengan pasangan yang sungguh menguras emosi. Lelah jiwa raga itu sungguhlah nyata untuk saya saat itu.
Maka tiap tahun dengan penghasilan yang lumayan saat itu agenda liburan menjadi sesuatu yang disiapkan jauh-jauh hari sebagai reward untuk diri sendiri, bisa lepas sejenak dari rutinitas. Meskipun sebetulnya liburan dengan pasangan yang emosinya tidak stabil juga sebetulnya sama sekali jauh dari rileks, saya harus bersiap dengan situasi ranjau yang terinjak bisa meledak kapanpun. Ketegangan sepertinya menjadi keseharian selama bertahun-tahun sehingga saya lupa rasanya bagaimana itu rileks, menikmati waktu saat ini disini tanpa pikiran yang sibuk berputar menata masa depan dan menyiapkan segala skenario antisipasi.
Baru belakangan ini saya rasanya bisa mulai menikmati kesibukan kerja tanpa harus mengalami kelelahan jiwa raga seperti dulu. Berlatih meditasi meskipun masih jauh dari kata ahli, namun saya sudah mulai merasakan perubahan yang berarti. Memang sudah tidak bekerja di media dengan ritme yang cepat atau melayani atasan yang seorang pejabat public, tapi multi peran yang saya jalani ini sejujurnya lebih banyak dari apa yang saya lakukan dulu. Berkarya di beberapa lembaga sekaligus, bisnis maupun nirlaba, ples klien-klien lain yang saya bantu sebagai konsultan freelance. Juga peran sebagai seorang ibu tunggal dengan anak yang beranjak remaja dengan segala dinamikanya. Dulu gak kebayang rasanya bisa kayak gini dan tetap waras. Apa sih bedanya?
Dulu saya belajar meditasi dengan niatan mencari rasa damai sesaat, sebagai pelarian dari penatnya kesibukan kerja dan jeda dari keriuhan tanggung jawab multi peran di rumah tangga. Namun ternyata setelah sekian tahun, saya memahami meditasi bukan hanya soal duduk merem, tapi aplikasi mindfulness di keseharian yang ditekankan disini menjadikan si praktisinya lebih aware dengan kondisi dirinya.
Pikiran juga auto ditata menjadi lebih sehat dan memiliki pola nalar yang lebih baik. Emosi lebih terkelola, serta perilaku juga menjadi lebih selaras, dan integritas menjadi terbentuk dengan sendirinya. Kesesuaian pikiran, kata-kata dan tindakan. Keren banget dampaknya ternyata. Sangat transformatif dan progresif. Tapi tentu saja jangan berharap hasil yang instan, prosesnya panjang dan tidak mudah. Saya juga masih berlatih dengan susah payah demi membentuk habit baru yang lebih konstruktif.
Saat ini juga saya bekerja dengan para atasan yang ahli meditasi dan melihat teladan secara nyata di depan mata, bagaimana pekerjaan mereka yang jauh lebih banyak dan multi dimensi kompleksitasnya itu bisa tertangani dengan baik, tanpa kehilangan kebahagiaan. Kepemimpinan berbasis kesadaran yang jernih, sebagai hasil dari praktik meditasi, menjadikan proses pengelolaan tim dan beban kerja dengan sederet paketannya bisa dijalankan dengan dengan optimal tanpa mengorbankan kesehatan mental dan fisik. Maka disini saya menyaksikan contoh sebaliknya dari yang saya pahami dulu, bahwa bekerja dengan bahagia itu sangat bisa. Asal tau caranya, dan mau menjalani proses berlatih dengan konsisten. Bekerja dengan tetap sehat jiwa itu seharusnya bisa diwujudkan oleh siapapun. Saya juga mau bisa seperti itu sepenuhnya.
Menjadi pemimpin tanpa burnout bisakah?
Perjalanan menjadi pemimpin berbagai jenis organisasi baik formal maupun informal, sedikit banyak memberikan warna dalam pertumbuhan saya sebagai pribadi. Dulu saya tidak mengerti korelasi antara sisi gelap dalam model kepemimpinan yang saya jalankan.
Menjadi pemimpin waktu itu bagi saya hanya berupa sederetan “wewenang lebih” sepaket dengan kewajiban yang melekat pada peran yang dijalankan, dengan maupun tanpa kompensasi. Memandang peran pemimpin sebagai sebuah kewajiban ini karena memang hampir semua pengalaman peran kepemimpinan yang saya jalankan adalah berdasar proses penunjukan, bukan atas upaya dan kesadaran saya untuk dengan sadar mengambil peran tersebut (termasuk jabatan di instansi saat ini). Hal ini berdampak pada motivasi saya dan bagaimana saya menjalankan peran tersebut.
Sisi gelap paling dominan adalah mental korban yang disebabkan oleh ketidakmampuan saya mengidentifikasi detail peran karena mental block tersebut. Bentuk respon yang muncul adalah; merasa serba salah, merasa tidak adil, merasa paling sibuk dan banyak pekerjaan, tidak adanya trust pada lembaga, ketua organisasi, atasan, staf dan team. Bentuk respon tersebut memanivestasi dalam laku berupa sulit berkolaborasi, manipulatif, tidak teliti, tidak sadar kapasitas sehingga merasa lebih bisa dan mau mengerjakan semua sendiri, egois dan tidak mampu menggunakan kritikan alih alih sebagai bahan bakar perbaikan , justru menganggap sebagai bentuk ancaman, tidak mampu menetapkan prioritas, dan sering berkonflik dengan unit lain.
Dalam kondisi ini sudah dipastikan saya menjadi sosok pemimpin yang selalu dalam kondisi burnout, lambat berpikir, lambat merespon, mudah emosi bahkan sampai ke dalam keluarga.
Beruntung dalam pembelajaran berbasis kesadaran Sigma Leadership ini saya diajak untuk mengidentifikasi drive sisi gelap dari setiap perwujudan laku kepemimpinan saya. Saya diajak menjadi pemimpin yang bersih dari sisi gelap sehingga arah kepemimpinan saya lebih jelas, dan mengurangi respon yang keliru dari setiap tantangan yang hadir. Pelan pelan mental korban ini dibenahi. Saat ini dibimbing menggunakan pikiran dengan lebih tepat, contoh simpel saat pikiran penuh karena merasa terlalu banyak tugas yang dibebankan, maka saya segera sadar bahwa itu adalah bentuk mental korban yang ujung ujungnya muncul sikap males, penundaan atau bahkan menghindari.
Ketika saya mulai mencoba mengatasi si mental korban tadi dan mulai bisa meniatkan untuk memetakan dengan jelas apa yang mesti saya kerjakan (salah satunya dengan coba menyusun tools to do list) ternyata sebenarnya saya masih banyak waktu untuk melakukan banyak karya bahkan dengan lebih ringan, saya juga lebih mampu berkolaborasi dengan lebih baik.
Tantangan masih sama tetapi saat ini sudah ada perbedaan bagaimana saya merespon tantantan tersebut.
Terimakasih Avalon
Pertama kali mengenal istilah emotional depletion pas kerja perdana sebagai sales di 5-star hotel. Tapi udah mengalami kelelahan mental ini sejak merantau untuk kuliah, cuma masih gak sadar. Menganggap ini situasi normal bagi anak kuliah untuk belajar sampai begadang lalu ngebul otaknya. Ambisi pengen cepet kelar ngejar kelulusan dengan nilai yang memuaskan biar dapat kerja dengan gaji gede selalu jadi bensin untuk terus bergerak maju selama kuliah. Butuh pengakuan eksistensi diri banget.
Sebagai sales, tidak pernah lepas dari target harian yang sebisa mungkin harus terpenuhi untuk closing monthly & yearly target. Mulai bikin target yang unrealistic untuk dapat recognition dari peers dan superior. Cukup beruntung bisa selalu memenuhi target bahkan melebihi target yang sudah diberikan. Berlanjut beberapa kali pindah kerja di tempat lainnya dengan modus operandi yang sama. Lelahnya semakin bertumpuk-tumpuk apalagi dengan posisi lebih tinggi harus lebih banyak melakukan networking setelah office hours.
Tidak hanya di pekerjaan, emotional drained juga terjadi di relationship dengan keluarga dan pasangan. Supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan memilih untuk diam, pura-pura mengalah dan setuju. Saat itu merasa ini adalah solusi yang terbaik, merasa masalah telah terselesaikan.
Giliran belajar meditasi yang beneran fokus pada pemurnian jiwa, sampah-sampah yang tertimbun dalam-dalam mulai muncul ke permukaan. Kewalahan banget, ambisi ingin cepat keluar dari roda samsara ini begitu meronta-ronta. Kembali ke self-mode yang selalu dilakukan di masa lalu untuk survive, tentunya tidak berhasil dan malah makin ambles. Otak pun rasanya stop di tempat alias brain fog.
Memimpin diri sendiri ala Sigma Leadership memerlukan kerendahhatian dan ketangguhan yang luar biasa besar untuk terus bisa bergerak maju. Fase saya saat ini mulai bisa menyadari ketika pattern survival mode kembali muncul meskipun masih banyak bablasnya.
Sangatlah tidak mudah untuk mengubah habit yang sudah dilakukan puluhan tahun dan diyakini, butuh proses yang panjang but I know for sure that it’s totally worth it.
Sangat relate dengan quote Sigma Leadership “A journey of self-growth, begins with a single step of consciousness”
Your Reaction: